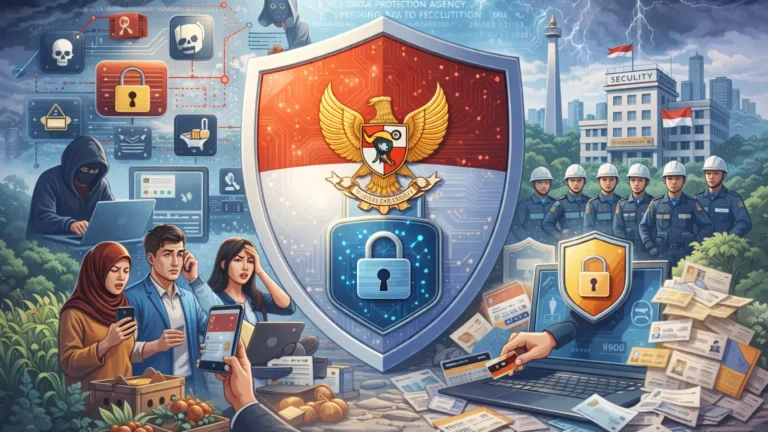Artikel ini ditulis oleh Septian Zeb Marion Siahaan, Fauzan Emir Pasha & Raden Mas Pranavadya Naufal Arundaya
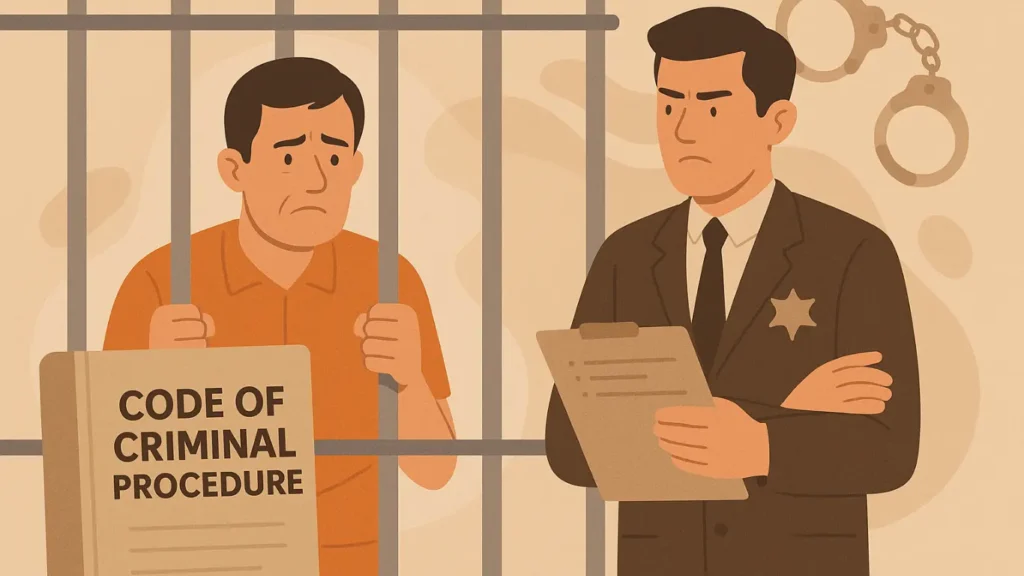
Penahanan merupakan tindakan hukum yang membatasi kebebasan seorang tersangka atau terdakwa dengan cara menjadikan mereka tahanan rutan, tahanan kota, atau tahanan rumah tersangka itu sendiri. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menempatkan penahanan sebagai instrumen luar biasa yang hanya dapat diterapkan apabila syarat-syaratnya tertentu terpenuhi. Agar memudahkan penyebutan dalam pembahasan selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai “KUHAP“). KUHAP secara tegas merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar penahanan tidak dijadikan tindakan berulang atau tindakan administratif semata, melainkan hanya dilaksanakan apabila terdapat kebutuhan yang mendesak dengan dasar hukum yang sah. Dalam kenyataannya, praktik penahanan sering kali tidak jelas pelaksanaannya. Hal ini terutama terlihat pada kasus penahanan selebgram Isa Zega di Polda Jawa Timur dalam perkara yang diberitakan sebagai dugaan pencemaran nama baik berbasis elektronik.
Kasus bermula dari laporan dugaan pencemaran nama baik berbasis elektronik terhadap Isa Zega di Polda Jawa Timur. Mengutip dari detikjatim yang menyatakan “Selebgram Isa Zega resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jatim. Hal ini usai gagal dilakukannya upaya restorative justice (RJ),” dapat diasumsikan bahwa pada 24 Januari 2025 penahanan dilakukan setelah upaya restorative justice tidak mencapai kesepakatan (Rahman, “Selebgram Isa Zega Resmi Ditahan Di Polda Jatim”). Selain itu, dalam berita yang sama pada tahap awal mengaitkan perkara dengan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pencemaran nama baik berbasis elektronik yang berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 hanya diancam maksimal dua tahun penjara. Agar memudahkan penyebutan dalam pembahasan selanjutnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai “UU ITE”). Selanjutnya, pada 8 Mei 2025, Pengadilan Negeri Kepanjen menjatuhkan pidana 3 tahun 6 bulan dengan pertimbangan yuridis yang merujuk pada Pasal 27 B jo. Pasal 45 ayat (10) UU ITE (ancaman pidana sampai 6 tahun).
Rangkaian peristiwa tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pertama, apakah penahanan pada tahap awal telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 KUHAP, khususnya apabila sangkaan pada saat itu masih terbatas pada Pasal 27A. Kedua, timbul isu kebijakan mengenai apakah kegagalan restorative justice turut mempengaruhi keputusan penahanan?
Baca juga: Penguatan Fungsi Undang-Undang Organik sebagai Alternatif atas Amendemen Konstitusi
Mengenai penahanan pada tahap awal, KUHAP secara tegas menetapkan prasyarat untuk dilakukannya penahanan, yakni syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, ataupun mengulangi tindak pidana. Sementara itu, syarat objektif merupakan ketentuan hukum yang berfungsi penentu atas dapat dilakukannya penahanan. Dengan demikian, penahanan hanya dapat diterapkan apabila tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih atau termasuk jenis kejahatan tertentu yang secara tegas disebutkan dalam pasal 21 ayat 4 KUHAP. Artinya, tidak setiap perkara serta-merta dapat berujung pada penahanan, harus terdapat keterkaitan yang jelas antara jenis kejahatan yang dituduhkan dengan kebutuhan proses hukum. Rumusan ini secara tegas tercantum dalam:
Pasal 21 ayat (1) KUHAP:
“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”
Pasal 21 ayat (4) KUHAP:
Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undangundang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086”
Pasal tersebut menegaskan bahwa syarat objektif adalah prasyarat yang menentukan dapat atau tidaknya penahanan dilakukan. Kedudukan syarat objektif sebagai “gerbang awal” memastikan bahwa pembatasan kebebasan hanya ditempuh ketika dasar hukumnya memenuhi ketentuan, sehingga penahanan tetap proporsional. Artinya, setiap aparat wajib menilai pemenuhan syarat objektif secara cermat, membandingkannya dengan tujuan proses peradilan, serta tidak melakukan penahanan bila syarat tersebut tidak tercapai.
Tahap berikutnya adalah menilai jenis tindak pidana yang disangkakan. Perubahan pada UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 memperjelas batas-batas sejumlah tindak pidana dan konsekuensi pemidanaannya. Pencemaran nama baik berbasis elektronik kini diatur dalam pasal 27A UU ITE, dengan bunyi berikut:
Pasal 27A UU ITE:
“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.
Pasal 45 ayat (4) UU ITE:
“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”
Perubahan pada pasal tersebut penting karena menegaskan sifatnya sebagai sebuah tindak pidana biasa dengan ancaman pidana paling lama dua tahun penjara, sehingga tidak memenuhi syarat objektif penahanan menurut Pasal 21 KUHAP. Sementara itu, Pasal 27 B mengatur mengenai pemaksaan dengan ancaman kekerasan atau ancaman pencemaran untuk memperoleh manfaat (pemerasan/ancaman berbasis elektronik), dengan bunyi sebagai berikut:
Pasal 27 B ayat (1) UU ITE:
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk: a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi hutang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”
Pasal 45 ayat (10) UU ITE
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi hutang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 B ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Berpacu pada pemberitaan detikjatim yang menyatakan “Terhadap IZ pada hari ini iya dilakukan penahanan, tersangka dijerat dengan Pasal 27 huruf A juncto pasal 45 ayat 4 dengan ancaman 2 tahun dan denda Rp 400 juta, (ditahan) di ruang tahanan Polda Jatim.”9 Dapat diasumsikan bahwa, penahanan yang dilakukan pada tahap awal tidak sah apabila dasar sangkaan yang digunakan adalah Pasal 27A UU ITE karena tidak memenuhi syarat objektif sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Perbedaan ancaman pidana antara Pasal 27A (maksimal dua tahun) dan Pasal 27 B (maksimal enam tahun) menentukan sah atau tidaknya penahanan. Dalam konteks kasus ini, hanya Pasal 27 B yang secara hukum memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan.
Keabsahan penahanan dinilai pada saat keputusan penahanan ditetapkan, bukan secara surut mengikuti perubahan pasal sangkaan maupun hasil pembuktian di kemudian hari. Untuk perkara dengan ancaman penjara maksimal dibawah 5 tahun seperti Pasal 27A, penahanan tidak sepatutnya digunakan dan wajib mengedepankan langkah penanganan yang proporsional sesuai KUHAP.
Setelah membahas aspek penahanan, kini pembahasan bergeser ke isu kebijakan yang muncul, yaitu apakah kegagalan restorative justice turut mempengaruhi keputusan penahanan? Restorative justice menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga para pihak, serta tokoh masyarakat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula. Agar memudahkan penyebutan dalam pembahasan selanjutnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Perpol”). Hal ini secara eksplisit disebutkan dalam:
Pasal 1 ayat (3) Perpol Nomor 8 Tahun 2021:
“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”
Perpol tersebut memberikan landasan normatif bagi penyelesaian perkara secara non-litigasi, yang dapat ditempuh apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi.
Berdasarkan pemberitaan oleh detikjatim pada 24 Januari 2025 yang menyatakan “Selebgram Isa Zega resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jatim. Hal ini usai gagal dilakukannya upaya restorative justice (RJ).” Hal ini menimbulkan persepsi publik bahwa kegagalan pelaksanaan restorative justice memiliki pengaruh dalam mengambil keputusan penahanan. Persepsi ini tidak selaras dengan desain Perpol yang dirujuk dalam artikel. Restorative justice dirancang sebagai mekanisme pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui kesepakatan damai yang adil, serta sebagai upaya untuk mengurangi dampak sosial dari suatu perkara. Oleh karena itu, kegagalan restorative justice tidak dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan tindakan ataupun memiliki pengaruh dalam penahanan, melainkan sebagai jalur alternatif penyelesaian perkara secara damai.
Menjadikan penolakan atau kegagalan restorative justice sebagai dasar penahanan justru bertentangan dengan tujuan mekanisme tersebut. Alih-alih mendorong pemulihan, pendekatan demikian berpotensi menciptakan insentif negatif bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Pelaku dapat khawatir bahwa ketidaktercapaiannya perdamaian dapat berkonsekuensi pada penahanan, sementara korban dapat dibebani ekspektasi bahwa persetujuan damai menentukan kerasnya reaksi penegak hukum. Situasi ini berisiko mengubah makna dari restorative justice itu sendiri, padahal Perpol menempatkannya sebagai jalur alternatif penyelesaian yang mengutamakan pemulihan. Artinya, keputusan untuk melakukan penahanan tidak bergantung pada hasil restorative justice, melainkan harus berlandaskan hukum acara yang berlaku.
Dengan permasalahan-permasalahan yang telah dibahas di atas, kemudian muncul pertanyaan baru. Apa langkah yang tersedia untuk merespons penahanan atau upaya paksa yang tidak sah? Jawabannya adalah pra-peradilan, yaitu mekanisme yang memberi kontrol yudisial cepat atas tindakan aparat penegak hukum. Dalam pra-peradilan, hakim hanya menilai keabsahan tindakan prosedural seperti dasar hukum, syarat, dan tata cara tanpa memeriksa pokok perkara atau menentukan benar-salahnya perbuatan. Tujuan utamanya melindungi hak asasi pihak yang dirugikan sekaligus memastikan akuntabilitas aparat. Fungsinya meliputi pengujian sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, penilaian atas penghentian penyidikan atau penuntutan (SP3 atau ketetapan sejenis), serta putusan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi bila tindakan dinyatakan tidak sah. Pemohon biasanya adalah pihak yang dirugikan (tersangka, keluarganya, atau kuasa hukumnya) atau pihak yang berkepentingan atas kelanjutan perkara, dan termohon, yaitu penyidik atau penuntut umum yang melakukan tindakan yang diuji. Kewenangan dari pra-peradilan ini bersifat terbatas pada kepatuhan prosedural dan dasar hukum. Dengan demikian, pra-peradilan menjadi sarana korektif yang efektif untuk memastikan due process tetap terjaga.
Merangkum keseluruhan pembahasan, inti analisis berpuncak pada dua pokok yang saling berkaitan, namun harus dibedakan secara tegas. Pertama, penahanan pada tahap awal wajib dinilai berdasarkan kerangka Pasal 21 KUHAP. Penahanan yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam pasal 21 KUHAP tidak memiliki dasar yang sah. Syarat-syarat tersebut menjadi ambang penentu atas boleh tidaknya dilakukan upaya penahanan. Dengan demikian, Pasal 21 KUHAP harus diterapkan secara disiplin agar tidak ada seorang pun yang hak kebebasannya dilanggar melalui penggunaan upaya penahanan.
Kedua, kegagalan restorative justice tidak dapat dijadikan dasar ataupun punya pengaruh dalam melakukan penahanan. Restorative justice merupakan mekanisme pemulihan dan penyelesaian damai antara para pihak, bukan alasan dilakukannya upaya paksa. Menjadikan ketidakberhasilan restorative justice sebagai alasan dilakukannya penahanan malah akan mengubah tujuan utamanya, yakni pemulihan yang adil dan pengurangan dampak sosial perkara.
Selain itu, menjadikan kegagalan restorative justice sebagai alasan penahanan berisiko melahirkan disinsentif bagi para pihak. Pelaku dapat menolak bernegosiasi karena khawatir ketiadaan kesepakatan dapat berpotensi berujung pada penahanan, sedangkan korban dapat terbebani ekspektasi bahwa persetujuan damai menentukan kerasnya respons penegak hukum. Oleh karena itu, keputusan penahanan harus berdiri di atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHAP.
Uraian di atas menunjukkan bahwa pra-peradilan berfungsi sebagai mekanisme koreksi upaya paksa yang menyimpang. Agar selaras dengan kerangka tersebut, keputusan penahanan harus berangkat dari syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP, bila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka penahanan tidak boleh dilakukan. Selain itu, kegagalan restorative justice tidak dapat dijadikan alasan, karena mekanisme itu bertujuan pemulihan, bukan pembatasan kebebasan. Dengan demikian, kepatuhan pada Pasal 21 KUHAP dan pemisahan tegas fungsi restorative justice menjadi kunci untuk menjaga due process, melindungi hak kebebasan, dan memastikan akuntabilitas penegak hukum.