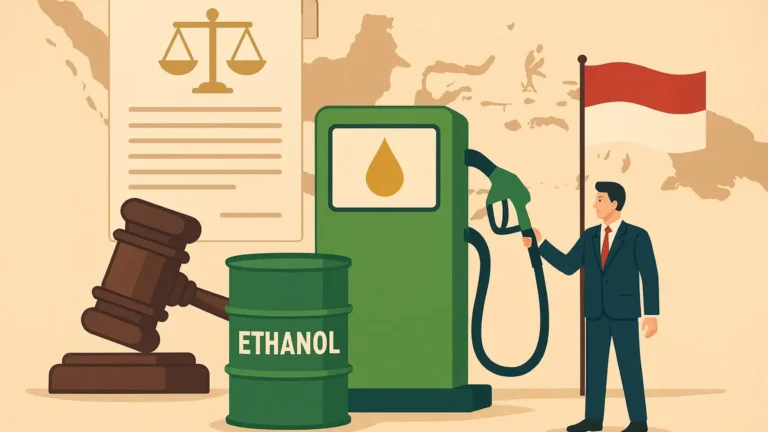Kilas Balik Stufenbau Theorie
Telah dijelaskan sebelumnya mengenai Stufenbau Theorie yang menjadi cikal bakal dari konstruksi hukum yang dianut oleh mayoritas negara saat ini. Teori tersebut menyatakan bahwa konstruksi norma hukum tersusun dari berbagai tingkatan yang saling bergantung. Norma yang lebih tinggi melahirkan turunan norma di bawahnya sekaligus memberikan legitimasi dan validitas norma yang lebih rendah tersebut. Setiap norma dapat ditarik untuk dicarikan sumber legitimasi dan validitasnya dari norma yang berada di atasnya. Ketika sampai pada pucuk yang tidak dapat ditarik lagi, maka itulah yang disebut oleh Hans Kelsen sebagai grundnorm atau norma dasar.
Keanehan yang terjadi dalam tata hukum (legal order) seperti terdapat norma yang lebih rendah malah bertentangan dengan norma yang berada di atasnya, maka harus “dipulihkan” dengan membatalkan norma yang lebih rendah tersebut. Adalah sebuah anomali ketika suatu norma yang lebih rendah justru “menentang” norma yang “melahirkannya”. Konsekuensi logis dari adanya hierarki norma hukum adalah adanya pengujian (termasuk di dalamnya adalah pembatalan) norma dan secara mutantis mutandis maka harus ada mekanisme untuk melakukan pengujian tersebut Dalam hal inilah, Hans Kelsen mengonstruksi turunan teorinya dengan menggagas perlu adanya lembaga peradillan konstitusi.
Yang menjadi objek perdebatan di kalangan ahli hukum tata negara tempo dulu sampai sekarang adalah mengenai legitimasi kewenangan peradilan konstitusi tersebut. Adalah tidak adil menurut kalangan yang menolak eksistensi lembaga peradilan konstitusi ketika norma hukum yang dirumuskan oleh kekuatan politik mayoritas harus “dikalahkan” oleh putusan dari peradilan konstitusi. Kelompok ini beranggapan bahwa peradilan konstitusi tidak mendapatkan legitimasi politik seperti halnya parlemen dalam menyusun norma hukum. Perdebatan mengenai hal tersebut akan dicoba untuk diulas dalam tulisan sederhana ini dan harapannya dapat menambah khazanah pembaca khususnya dalam hal ketatanegaraan.
Konstruksi Lembaga Peradilan Konstitusi
Lembaga peradilan konstitusi sebagai suatu konsep tidaklah muncul secara tiba-tiba tanpa ada yang mendasarinya. Konsep lembaga peradilan konstitusi lahir sebagai konsekuensi logis dari adanya Stufenbau Theorie mengenai hierarki norma hukum. Struktur tata hukum diposisikan sebagai suatu sistem yang karenanya keanehan seperti menyimpangnya suatu norma hukum wajib dipulihkan. Pemulihan tersebut dapat dilakukan dengan pembatalan norma yang bersangkutan dan untuk sampai pada pembatalan tersebut, maka perlu adanya mekanisme pengujian.
Mekanisme pengujian ini pastinya memerlukan “batu uji” agar norma yang diuji validitasnya dapat dinilai apakah valid sehingga tidak dibatalkan atau tidak valid sehingga wajib dibatalkan. Oleh karena norma yang diuji validitasnya tersebut pasti memiliki norma yang lebih tinggi, maka norma yang lebih tinggi tersebutlah yang menjadi batu uji. Tidaklah logis jika dilakukan sebaliknya yang mana suatu norma diujikan dengan batu ujinya adalah norma yang sederajat atau bahkan yang lebih rendah. Ini karena dalam norma yang sederajat itu tidak terjadi penurunan legitimasi dari suatu norma ke norma yang lain. Adapun kondisi kedua yaitu norma yang lebih tinggi diujikan dengan norma yang lebih rendah sebagai batu ujinya adalah sebuah kesalahan berpikir atau logical fallacy. Bagaimana mungkin suatu norma yang lebih tinggi harus “dikalahkan” dengan norma yang ia “lahirkan’’ dan berikan legitimasinya.
Setelah dikonstruksikan bahwa mekanisme pengujian norma hukum adalah suatu keniscayaan sebagai turunan dari Stufenbau Theorie, maka perlu ada lembaga yang melaksanakan mekanisme tersebut. Suatu mekanisme sebagus dan selogis apapun hanya akan menjadi rel kosong tanpa lokomotif ketika tidak ada lembaga yang berwenang untuk menjalankannya. Di kalangan ahli hukum tata negara, ada kelompok yang berpandangan bahwa mekanisme pengujian ini seharusnya dilaksanakan oleh lembaga yang membuat norma hukum itu sendiri. Kalangan lainnya, Hans Kelsen berada di posisi ini, berpandangan bahwa mekanisme tersebut harus diberikan oleh lembaga lain di luar lembaga yang membuat norma hukum tersebut.
Argumen kelompok pertama adalah bahwa lembaga yang membuat suatu norma hukum jauh lebih mengetahui norma hukum tersebut dibandingkan lembaga lain. Jika lembaga lain diberikan kewenangan untuk melaksanakan mekanisme pengujian ini, maka hal itu dapat dinilai sebagai suatu intervensi kewenangan dan mencederai prinsip separation of power atau pemisahan kekuasaan. Kelompok ini juga berpandangan bahwa lembaga yang membuat suatu norma hukum, dalam hal ini adalah parlemen, memiliki legitimasi yang jauh lebih besar daripada lembaga lainnya. Dengan kata lain, maka lembaga di luar parlemen yang direncanakan akan berwenang menguji suatu norma hukum harus memiliki legitimasi yang sekurang-kurangnya sama dengan parlemen tersebut.
Lembaga peradilan konstitusi dipandang oleh kelompok pertama ini juga sebagai bentuk pelanggaran prinsip kedaulatan rakyat. Pasalnya adalah lembaga peradilan ini tidak diisi oleh orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga dipandang bahwa legitimasinya jauh di bawah legitimasi parlemen. Namun di sisi lain, putusan dari lembaga peradilan ini ternyata diposisikan setara dengan norma hukum yang dibentuk oleh parlemen. Inilah yang menjadi argumen pokok dari penolakan terhadap eksistensi lembaga peradilan yang berwenang menguji norma hukum.
Di sisi yang berlawanan, kelompok kedua berargumen bahwa kebutuhan akan lembaga peradilan yang berwenang menguji suatu norma hukum bersifat sangat mendesak. Kehadiran lembaga peradilan ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang dari parlemen sebagai pembentuk norma hukum. Tanpa adanya lembaga penyeimbang ini (sebagai perwujudan prinsip check and balances), maka dikhawatirkan akan terjadi tirani mayoritas. Kekuatan parlemen dalam membentuk norma hukum berasal dari suara politik mayoritas dan karenanya akan sangat potensial terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan kelompok mayoritas tersebut.
Baca juga: Stufenbau Theorie Hans Kelsen dalam Kacamata Hukum Indonesia
Tanpa kehadiran lembaga peradilan yang independen dalam menyeimbangkan kekuatan politik, tidak akan ada batasan bagi kekuatan politik di parlemen untuk membentuk norma hukum yang notabane hanya menguntungkan pihak mereka saja. Kelompok minoritas yang kurang mendapatkan suara di kekuatan politik parlemen, akan sangat rentan dicaploki hak-haknya. Kehadiran lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengujian norma hukum dapat memberikan perlindungan terutama bagi kelompok minoritas ini yang kurang mendapatkan kekuatan politik.
Praktik Pengujian Norma Hukum di Dunia Modern
Terlepas dari perdebatan dua kelompok yang saling bertolak belakang tersebut, nyatanya praktik pengujian norma hukum ini sudah diamini oleh mayoritas negara di dunia. Pengujian norma hukum yang diikuti dengan kewenangan pembatalannya juga telah dipraktikkan dengan berbagai model. Setidaknya terdapat dua model pengujian yang populer dan menjadi kiblat bagi praktik pengujian norma hukum dengan tidak menutup fakta terdapatnya beberapa model pengujian lainnya.
- Model Amerika Serikat
Dalam sistem hukum Amerika Serikat, kekuasaan kehakiman berpucuk pada satu lembaga yaitu Supreme Court. Kewenangan Supreme Court dalam mengujikan norma hukum dalam suatu perundang-undangan dipecah ke semua pengadilan di bawah Supreme Court tersebut. Disebarnya kewenangan pengujian tersebut ke lingkungan pengadilan di bawah Supreme Court menjadikan model pengujian ini disebut dengan model difusi.
Di bawah Supreme Court, Pengadilan Federal dan Pengadilan Distrik berwenang melakukan pengujian yang disebut judicial review di samping kewenangannya dalam mengadili proses litigasi biasa. Proses litigasi biasa seperti sengketa kerugian antara individu dapat dinaikkan menjadi proses judicial review manakala hakim menemukan fakta bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan norma hukum suatu perundang-undangan. Proses judicial review yang berangkat dari kasus konkret ini merupakan ciri khas dari concrete review.
Jika merunut secara historis, memang akan ditemukan fakta bahwa model judicial review ini bermula dari kasus sengketa antara Marbury vs Madison pada 1803. Dari sengketa tersebut, lahirlah doktrin yang dikeluarkan oleh Chief Justice of Supreme Court (Ketua Mahkamah Agung) John Marshall bahwa lembaga peradilan berwenang mengujikan norma hukum. Dasar argumentasinya adalah bahwa lembaga peradilan wajib menjaga konstitusi sebagai sumber hukum pertama sehingga norma hukum yang berada di bawahnya wajib dibatalkan manakala bertentangan dengan konstitusi.
- Model Kelsenian
Hans Kelsen di samping mengonstruksi Stufenbau Theori-nya, ia juga menginisiasi pembentukan lembaga peradilan konstitusi yang berdiri sendiri. Model yang diinisasi oleh Kelsen ini berbeda dengan praktik di Amerika Serikat yang mana kekuasaan kehakiman termasuk pengujian memiliki satu atap yaitu Supreme Court. Peradilan Konstitusi yang disebut sebagai Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) digagas oleh Kelsen sebagai peradilan khusus yang menangani judicial review dengan mengujikan undang-undang terhadap konstitusi.
Model pengujian yang menjadi kewenangan Constitutional Court ini pada dasarnya adalah pengujian abstrak (abstract review) yaitu pengujian dilakukan langsung terhadap suatu norma tanpa melalui proses litigasi biasa. Jika model pengujian Amerika berangkat dari kasus konkret, maka model Kelsenian berbeda yaitu tidak mensyaratkan adanya kasus konkret. Norma hukum tidak perlu sampai konkret menyebabkan kerugian sehingga dilakukan pengujian, melainkan juga dapat jika baru sebatas potensial selama memiliki kasualitas antara norma hukum dengan kerugian tersebut.
Ordinary court (pengadilan biasa) dalam model Kalsenian ini memang tidak berwenang seperti dalam model Amerika untuk melakukan pengujian norma hukum. Namun menurut Kelsen, pengadilan biasa tetap dapat turut berperan yaitu dengan diberikan kewenangan untuk menolak menerapkan suatu norma hukum yang diyakini oleh hakim bahwa norma hukum tersebut inkonstitusional (bertentangan dengan konstitusi). Model Kelsenian ini dinilai lebih dapat memberikan kepastian hukum karena menghadirkan kontrol peradilan terhadap pembentuk undang-undang. Dengan adanya dua jalur pengujian, yaitu abstrak sekaligus konkret ini, maka penerapan konstitusi lebih dapat terjamin dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan. Rezim otoriter yang menggunakan tirani mayoritas juga dapat dicegah oleh mekanisme pengujian dengan model Kalsenian ini.
Peradilan Konstitusi dalam Penerapannya di Indonesia
Dari dua model utama judicial review di atas, Indonesia pada dasarnya menganut model Kalsenian dengan mendirikan lembaga peradilan konstitusi independen yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Kehadiran MK dalam sistem hukum Indonesia dapat dilacak dari perubahan UUD 1945 khususnya pada perubahan tahap ketiga dan diturunkan dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Dari kewenangannya, yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, dapat ditarik benang merah bahwa model Kalsenian-lah yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.
Di samping menerapkan model Kalsenian tersebut, dapat dilihat juga aspek “difusi” atau penyebaran kewenangan dalam melakukan judicial review. Dalam sistem hukum Indonesia, judicial review dibagi menjadi dua berdasarkan batu ujinya yaitu uji konstitusionalitas dan uji legalitas. Uji konstitusionalitas adalah pengujian dengan menggunakan konstitusi sebagai batu ujinya. Pengujian jenis ini merupakan kewenangan MK sebagaimana yang telah dijelaskan yaitu mengujikan undang-undang terhadap UUD 1945. Sedangkan uji legalitas adalah pengujian dengan menggunakan undang-undang sebagai batu ujinya. Pengujian jenis ini dilakukan dengan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangannya pun di-“difusi”-kan yaitu diberikan kepada Mahkamah Agung (MA).
MA dalam sistem hukum Indonesia membawahi beberapa jenis pengadilan, namun pengadilan biasa yang berada di bawah MA tidak diberikan kewenangan sebagaimana yang digagas oleh Kelsen. Pengadilan biasa tidak diberikan kewenangan melakukan pengujian secara langsung dalam proses litigasi yang berangkat dari kasus konkret. Kewenangan yang dimiliki pengadilan biasa adalah sebatas pada menerapkan norma hukum dan menggali nilai-nilai keadilan tanpa menyentuh aspek pengujian norma hukum yang akan diterapkan tersebut.
Konklusi
Stufenbau Theorie yang digagas Hans Kelsen secara logis menuntut adanya mekanisme pengujian norma hukum ketika terjadi pertentangan antara norma yang lebih tinggi dan rendah. Dalam hal ini, Kelsen menggagas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan independen dalam melakukan pengujian tersebut. Di antara model pengujian lainnya, model yang digagas Kelsen inilah yang diterapkan di Indonesia. Namun dalam penerapannya, model pengujian Kalsenian ini dimodifikasi agar terjadi penyesuaian sebagaimana Stufenbau Theorie juga dilakukan hal serupa.
Sumber Bacaan
- Hans Kelsen, The General Theory of Law and State
- Idul Rishan, Teori dan Hukum Konstitusi
- Jacob T. Levy, “E Separation of Powers and the Challenge to Constitutional Democracy”
- Mirza Satria Buana, Perbandingan Hukum Tata Negara (Filsafat, Teori, dan Praktik)