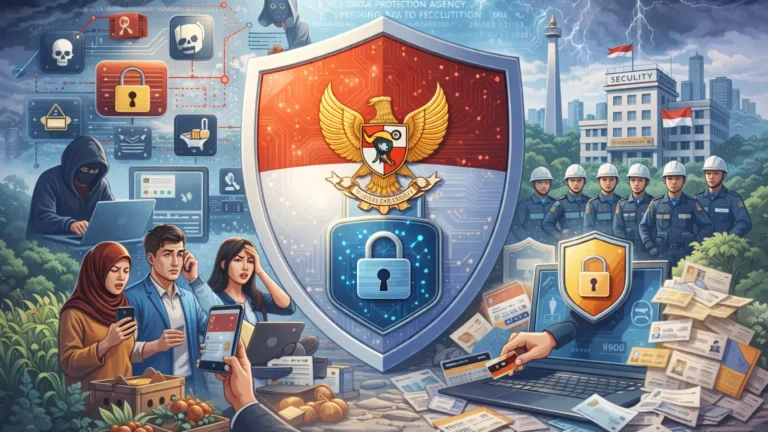Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai 2029 memang menuai kontroversi, terutama dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tapi sejujurnya, bukan Mahkamah Konstitusi yang patut dipertanyakan akal sehat konstitusionalnya, melainkan justru sebagian pihak di DPR yang terlihat gelagapan menghadapi logika hukum yang jauh lebih tajam dari yang bisa mereka pahami. Putusan ini bukan sekadar tafsir sempit, melainkan strategi konstitusional untuk menyelamatkan kualitas demokrasi elektoral kita yang, pada Pemilu 2024 lalu, telah dicabik-cabik oleh praktik curang, politik uang, dan penyalahgunaan kekuasaan yang terang-terangan. Anehnya, dua lembaga yang digaji negara untuk mengawasi proses pemilu yakni KPU dan Bawaslu justru seperti kehilangan taring. Pelanggaran yang tampak nyata di depan publik justru tidak pernah “ditemukan” dalam proses resmi. Dalih demi dalih dilontarkan untuk menutupi kelemahan pengawasan, hingga publik pun menyimpulkan bahwa fungsinya tak lebih dari sekadar formalitas.
Di tengah keputusasaan masyarakat terhadap proses elektoral yang kotor dan sistemik itu, MK hadir dengan keputusan monumental. Pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah menjadi win-win solution yang jernih secara hukum dan bijak secara politik. Ini adalah langkah struktural agar rakyat bisa benar-benar fokus dalam memilih wakilnya, tanpa harus kebingungan menghadapi lima kotak suara sekaligus, yang selama ini justru membuka ruang kekacauan administratif dan manipulasi suara. Lalu apa dasar konstitusionalnya? Sangat jelas di atur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal ini tidak pernah menyatakan bahwa seluruh jenis pemilu baik nasional maupun daerah harus digelar serentak pada hari yang sama. Yang diwajibkan adalah lima tahunan. Adapun bentuk, tahapan, dan teknis pelaksanaannya adalah ruang tafsir hukum yang diberikan kepada pembentuk undang-undang, dan jika tafsir tersebut menyimpang, maka MK-lah yang punya kewenangan konstitusional untuk mengoreksinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24C UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD.
MK tidak sedang menciptakan hukum baru, melainkan menyempurnakan hukum agar selaras dengan cita konstitusi: demokrasi yang jujur, adil, dan mengembalikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Jeda dua setengah tahun antara Pemilu Nasional dan Pilkada sebagaimana dimaksud MK bukanlah rekayasa Indonesia semata. Ini adalah model umum di banyak negara demokrasi maju seperti Jerman, Kanada, dan India yang secara terbukti mampu mencegah tumpang tindih otoritas dan memastikan evaluasi objektif terhadap kinerja pemerintah pusat maupun daerah.
Mereka yang menolak putusan MK, terutama dari DPR, sebaiknya mawas diri. Sejumlah anggota dewan dengan mudah menuduh MK melanggar Pasal 22E dan Pasal 18 UUD 1945, tapi lupa bahwa praktik selama ini justru menjadikan pemilu sebagai panggung politik elite nasional semata, tanpa kepedulian terhadap otonomi lokal. Di lapangan, seringkali caleg DPR hanya “menumpang hidup” pada kerja keras caleg DPRD tingkat I dan II. Istilah “tandem” yang kerap mereka dengungkan tidak lebih dari bualan politik, sebab faktanya tidak semua caleg di tingkat bawah benar-benar mendapat dukungan atau keadilan distribusi dari atasannya.
Maka, ketika DPR mengatakan pemisahan pemilu akan menimbulkan “kekosongan pemerintahan daerah”, perlu kita ingat: Indonesia sudah pernah mengalami hal ini pada 2023 dan 2024. Masa jabatan kepala daerah berakhir sebelum Pilkada digelar, dan negara tidak bubar karenanya. Justru penjabat kepala daerah (Pj) mampu menjalankan roda pemerintahan secara administratif tanpa harus merusak ketatanegaraan. Lantas bagaimana dengan DPRD timbul pertanyaan? Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan antara Pemilu nasional dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukanlah pelanggaran terhadap prinsip lima tahunan dalam UUD 1945. Pemisahan ini justru menjadi bentuk penyelarasan antara substansi konstitusi dengan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Prinsip “setiap lima tahun sekali” sebagaimana dimuat dalam Pasal 22E UUD 1945 tidak harus dimaknai secara kaku sebagai keserentakan waktu pelaksanaan, melainkan sebagai siklus kekuasaan yang berjalan teratur tanpa adanya perpanjangan kekuasaan yang inkonstitusional. Ketika masa jabatan kepala daerah berakhir sebelum Pilkada tahun 2031, pengisian jabatan akan dilakukan melalui mekanisme penunjukan Penjabat (PJ) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Dengan demikian, meski pelaksanaan Pilkada berlangsung di tahun ke-7 sejak pilkada sebelumnya, prinsip lima tahunan tetap terpenuhi secara substansial, karena tidak ada perpanjangan jabatan maupun kekosongan pemerintahan, dan seluruh proses tetap berada dalam koridor hukum serta legitimasi konstitusional yang sah.
Pemisahan jadwal antara Pemilu dan Pilkada yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi menimbulkan konsekuensi logis terhadap masa jabatan anggota DPRD yang dapat melampaui lima tahun. Meski secara tekstual UU No. 10 Tahun 2016 mengatur masa jabatan lima tahun, tetapi norma tersebut tidak bersifat kaku karena tetap memberi ruang untuk keberlanjutan pemerintahan hingga anggota DPRD hasil pemilu berikutnya dilantik. Kekhawatiran DPR akan kekosongan legislatif daerah justru terkesan mengada-ada, sebab sistem ketatanegaraan kita tidak mengenal mekanisme pengangkatan Penjabat DPRD, dan hukum positif telah menjamin mereka tetap menjabat sampai diganti secara sah. Maka, perpanjangan jabatan de facto ini bukanlah pelanggaran hukum, melainkan bentuk adaptasi konstitusional yang sah terhadap perubahan siklus demokrasi. Sebaliknya, pemisahan pemilu membuka ruang bagi rakyat untuk memilih lebih rasional dan tidak terseret arus politik transaksional dalam satu tarikan napas.
Baca juga: Demi Siapa Abolisi dan Amnesti Itu Diberikan?
Apakah putusan MK ini mutlak? Tentu tidak. Tapi secara yuridis, konstitusional, dan sosiologis, ia hadir tepat waktu dan sangat diperlukan. Putusan ini justru memaksa elite politik berhenti memonopoli tafsir UUD 1945 dan mulai melihat demokrasi bukan sekadar permainan kotak suara, tetapi juga kualitas pemilih dan sistem yang menopang kedaulatan rakyat. Mereka yang menolak putusan MK bukan hanya menolak logika hukum, tapi juga menolak pembelajaran demokrasi dari sejarah kecurangan yang sudah sangat mencolok mata. Kritik dari DPR yang menyebutnya “tidak sesuai konstitusi” lebih mencerminkan kebutaan terhadap semangat konstitusi ketimbang pembelaan terhadap demokrasi.