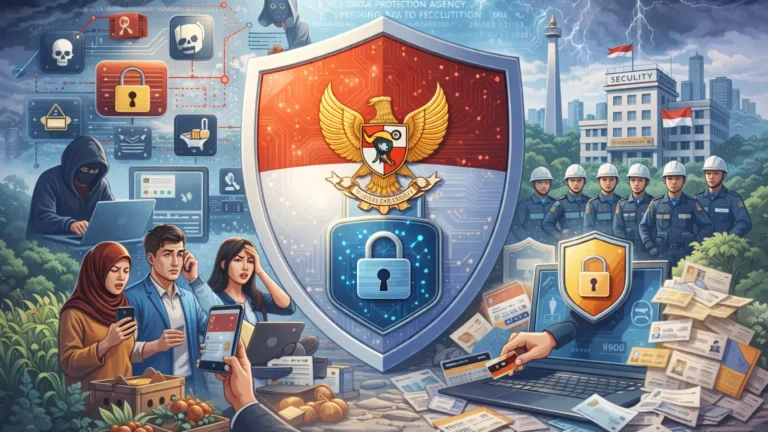Artikel ini ditulis oleh Muhammad Baihakii, Aaliyah Ramdhani & Kasandra Khairani Hisan

A. Background & Problem Formulation
Kehadiran Regulasi Anti-Deforestasi Uni Eropa atau EUDR (European Union Deforestation Regulation) menandai sebuah babak baru dalam hukum lingkungan global yang tidak dapat lagi dihindari oleh negara-negara produsen komoditas. Regulasi ini bukanlah sekadar kebijakan dagang, melainkan sebuah instrumen hukum yang lahir dari urgensi krisis iklim global akibat deforestasi. EUDR berdiri di atas tiga pilar wajib yang fundamental, yakni larangan produk dari lahan deforestasi, kewajiban ketertelusuran (traceability) hingga ke koordinat geografis plot lahan, serta jaminan legalitas produk yang harus patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di negara asal.1 Langkah ini menjadi sangat penting karena secara hukum memaksakan praktik uji tuntas (due diligence) di sepanjang rantai pasok, sekaligus merefleksikan prinsip bahwa negara konsumen memiliki tanggung jawab hukum atas dampak ekologis yang terjadi di negara produsen.
Secara ideal, hukum harus berfungsi sebagai instrumen utama negara untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan menjamin hak asasi manusia yang melekat padanya. Di Indonesia, amanat ini tertuang jelas dalam konstitusi yang mengakui hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi.2 Kewajiban ini dipertegas lebih lanjut dalam berbagai peraturan, yang menempatkan negara sebagai penjaga ekosistem dari kerusakan. Dengan demikian, kewajiban hukum untuk melindungi lingkungan seharusnya setidaknya seimbang, jika tidak mendahului kepentingan ekonomi sesaat. Lingkungan bukanlah pelengkap pembangunan, melainkan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan antar-generasi.
Ironisnya justru terdapat jurang yang dalam antara hukum di atas kertas (de jure) dan realitas di lapangan (de facto). Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum lingkungan yang relatif memadai, implementasi dan penegakannya kerap lemah dan tidak serius. Bukti nyata dari ironi ini tercermin dari data deforestasi itu sendiri. Analisis yang dilakukan oleh Forest Watch Indonesia (FWI), dengan memadukan data tutupan hutan tahun 2017 dengan data kehilangan hutan dari Universitas Maryland, menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Hasilnya, sepanjang periode 2018-2020 saja, Indonesia telah kehilangan sekitar 680 ribu hektar hutan alam, yang setara dengan laju rata-rata sebesar 227 ribu hektar per tahun.3 Angka ini menjadi cerminan konkret Indonesia tidak pernah menganggap serius perlindungan lingkungan hidup.
Mematuhi standar EUDR saat ini memang terasa sulit, namun bukan berarti mustahil. Kesulitan tersebut tidak hanya datang dari permintaan EUDR yang berlebihan, melainkan dari fondasi tata kelola kita yang memang sudah rapuh, yaitu karena masalah internal menahun seperti tumpang tindih kepemilikan lahan yang belum terselesaikan dan rumitnya proses sertifikasi legalitas bagi jutaan petani kecil.4 Pada dasarnya, tuntutan seperti ketertelusuran dan verifikasi legalitas lahan adalah standar dasar tata kelola yang baik. Fakta bahwa kita tergagap untuk memenuhinya justru menunjukkan seberapa jauh Indonesia tertinggal, bahkan dari prasyarat tata kelola yang paling wajar sekalipun.
Kondisi ini menempatkan Indonesia pada sebuah simpang jalan yang krusial. Di satu sisi, terdapat tekanan ekonomi dan narasi kedaulatan yang kuat untuk menolak implementasi EUDR. Dimana, regulasi ini dipandang sebagai hambatan non-tarif karena menetapkan syarat teknis yang sangat rumit dan berbiaya tinggi, sehingga berpotensi menghambat ekspor. Kebijakan ini juga dianggap tidak adil jika merujuk pada prinsip Common But Differentiated Responsibilities (CBDR), yang menegaskan bahwa tanggung jawab lingkungan antara negara maju dan berkembang tidak bisa disamaratakan begitu saja. Namun di sisi lain, ada keharusan moral dan hukum untuk merespons tuntutan global ini sebagai momentum untuk melakukan reformasi tata kelola domestik yang telah lama tertunda. Hal tersebut kemudian berdampak pada keputusan terbaru yakni adanya penundaan penerapan EUDR yang seharusnya diterapkan pada 30 Desember 2024, menjadi 30 Desember 2025. Dengan demikian, Dilema ini tidak berhenti pada soal menerima atau menolak EUDR, melainkan juga menuntut jawaban konkret bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia menghadapi masalah ini.
B. Analysis
Ditundanya pemberlakuan EUDR ini tentunya menimbulkan sebuah pertanyaan “Bagaimana persiapan Indonesia dalam mempersiapkan penerapan EUDR di tahun mendatang? Ternyata, berdasarkan hasil analisa negara Indonesia masih belum siap untuk menerapkan kebijakan EUDR baik dari sisi regulasi maupun sisi teknis. Misalnya, dalam pengaturan regulasi yang masih kendor untuk membahas mengenai larangan deforestasi telah membuat Indonesia selama 75 tahun terakhir kehilangan 70% hutan di Sumatera dan 50% hutan Kalimantan yang digunakan untuk perkebunan sawit, kayu, dan pertambangan mineral.5 Selain itu, berdasarkan beberapa argumentasi yang disampaikan oleh perwakilan Indonesia mengenai pemberlakuan EUDR ini akan membuat para petani smallholders kehilangan mata pencahariannya tentulah tidak dapat terus menerus menjadi argumentasi untuk tidak diterapkannya mekanisme yang cukup baik untuk perbaikan lingkungan secara global.
Saat ini, yang dibutuhkan adalah peran bersama antara pemerintah Indonesia dengan pihak uni eropa untuk saling bahu membahu memperbaiki lingkungan global. Misalnya, berdasarkan data lapangan yang terjadi di Kalimantan Timur melalui program SHINES telah berhasil untuk untuk memberdayakan ratusan petani untuk mendapatkan sertifikasi dan akses pasar internasional, sekaligus meningkatkan posisi tawar mereka. Dengan demikian, risiko eksklusi yang selama ini dikhawatirkan dapat diubah menjadi peluang ekonomi jika ada kombinasi kebijakan inklusif, pendanaan transisi dari Uni Eropa, serta komitmen industri dalam menjalin kemitraan langsung dengan smallholders.6
Namun, dibalik kebijakan EUDR yang terlihat akan membawa dampak positif bagi lingkungan ternyata terdapat permasalahan dalam kerangka hukum perdagangan internasional karena telah melanggar ketentuan prinsip non diskriminasi WTO dengan melanggar beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:
- Pasal 1 GATS 1994 dan article II GATS.
Melanggar prinsip non-diskriminasi perdagangan antar negara (Most Favored Nation/MFN) karena telah memberlakukan kebijakan yang mendiskriminasi terhadap barang dan jasa sejenis yang diimpor suatu negara dari berbagai negara. - Pasal 3 GATT 1994 dan article XVII GATS.
Melanggar prinsip non diskriminasi barang sejenis dan jasa antara yang diimpor dengan produksi domestik (National Treatment/NT) karena dalam konteks ini EUDR hanya memberlakukan untuk produk impor namun tidak diberlakukan untuk produksi domestik. - Pasal IX dan article II GATT 1994.
Menjadi hambatan non tarif (Non tariff Barrier) karena uni eropa membuat kebijakan dalam bentuk kuota, pembatasan, prosedur atau syarat tertentu untuk membatasi masuknya barang impor dengan tujuan untuk melindungi industri/komoditi domestik. - Pasal I, III, IX, X, XI, dan XX GATT.
Melanggar prinsip Technical Barrier to Trade (TBT) karena membuat hambatan hal teknis seperti kualitas produk, pengepakan, penandaan, dan persyaratan keamanan yang harus dilakukan untuk sesuai dengan teknis yang diberikan oleh Uni Eropa.7
Berdasarkan analisis tersebut, menjadi hal yang perlu didiskusikan kembali oleh pemerintah Indonesia apakah akan tetap mengikuti dan menerapkan kebijakan EUDR sebagai upaya memperbaiki tata kelola lingkungan di Indonesia khususnya untuk mengurangi deforestasi yang kian parah atau akan menganggap kebijakan EUDR tersebut sebagai pelanggaran ketentuan diskriminasi WTO. Biarlah hal tersebut menjadi kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah yang berwenang, namun yang perlu digaris bawahi adalah dengan adanya kebijakan EUDR maupun tidak pemerintah wajib untuk terus menekan angka kerusakan lingkungan di Indonesia.
Maka sebagai bentuk antisipasi dan langkah penyesuaian terhadap kemungkinan implementasi EUDR, Indonesia telah melakukan sejumlah inisiatif yang mencerminkan komitmen untuk memperbaiki sistem tata kelola komoditas dan keberlanjutan. Beberapa langkah strategis tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Kerjasama Joint Task Force dengan Malaysia
Indonesia bersama dengan Malaysia, dan Uni Eropa juga telah sepakat untuk membentuk Gugus Tugas Ad Hoc (Ad Hoc Joint Task Force) on EUDR guna mengatasi berbagai hal terkait dengan pelaksanaan EUDR yang dihadapi Indonesia dan Malaysia. Gugus tugas tersebut juga dibentuk untuk mengidentifikasi solusi dan penyelesaian yang terbaik terkait implementasi EUDR.8
Kick off meeting JTF dilakukan pada 4 Agustus 2023 di Jakarta, Indonesia. Dalam pertemuan tersebut disepakati lima workstreams yang menjadi fokus terkait implementasi aturan EUDR, yaitu Inclusivity of smallholders in the supply chain, Relevant certification schemes, Traceability, Scientific data on deforestation and forest degradation, dan Protection of privacy data.9
2. National Dashboard
Pemerintah Indonesia mengembangkan National Dashboard Indonesia (Dasbor Nasional) sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola komoditas berkelanjutan dan membangun sistem traceability sesuai ketentuan EUDR. Inisiatif ini dituangkan melalui Keputusan Menko Perekonomian (Kepmenko) Nomor 178 Tahun 2024 tentang Komite Pengarah Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan Indonesia.
Namun, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Satya Bumi, Greenpeace Indonesia, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), dan Koalisi Transisi Bersih pada Selasa 17 Desember 2024, sejumlah kritik disampaikan terhadap kebijakan tersebut. Perwakilan organisasi yang hadir menilai Dasbor Nasional belum menunjukkan transparansi yang memadai.
Dewan Nasional SPKS, Mansuetus Darto, menilai bahwa pemerintah sebaiknya tidak menghabiskan waktu untuk membangun sistem baru yang belum tentu efektif. Ia menekankan bahwa penguatan traceability, kapasitas sumber daya manusia birokrasi, terutama di daerah, serta dukungan terhadap pelaku usaha jauh lebih mendesak. Selain itu, menurutnya, tidak ada kewajiban bagi negara produsen untuk membangun sistem informasi sendiri, karena Uni Eropa-lah yang bertanggung jawab menyiapkan dan mendistribusikan sistem tersebut. Sayangnya, sistem ini tidak akan tersedia secara terbuka untuk publik, melainkan hanya dapat diakses oleh konsumen atau otoritas yang mendapatkan izin melalui Dasbor Nasional. Padahal, dampak aktivitas industri komoditas ekspor seperti sawit dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal dan lingkungan.
Sejalan dengan hal tersebut, Rambo Susanto menyarankan agar pemerintah mengintegrasikan berbagai sistem informasi yang telah ada sebelumnya, seperti SIPERIBUN, ESTDB, INATRADE, CEISA, dan PCOPI, sebagai basis data utama. Menurutnya, fokus utama seharusnya diarahkan pada perbaikan tata kelola komoditas sawit secara menyeluruh, bukan pada pembangunan sistem baru yang belum terbukti efektif.
Kritik serupa juga disampaikan oleh peneliti Satya Bumi, Sayyidati Haya Afra. Ia menegaskan bahwa jika tujuan utama pemerintah adalah memperkuat keberlanjutan komoditas, maka transparansi dan kredibilitas data seharusnya menjadi prinsip utama dalam pembangunan Dasbor Nasional.10
3. Upaya Verifikasi: Menjembatani ISPO dengan Persyaratan EUDR
Sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan, Indonesia telah mengembangkan skema sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Skema ini menilai kelayakan usaha perkebunan sawit dari tiga aspek utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sertifikasi ISPO diberikan oleh lembaga independen yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sehingga menjamin objektivitas dalam proses verifikasi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020, ISPO memiliki tujuh prinsip dan kriteria utama, yaitu:
- Kepatuhan terhadap hukum, termasuk legalitas lahan dan usaha.
- Praktik perkebunan yang baik, mencakup perencanaan, budidaya, hingga pengolahan.
- Pengelolaan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, termasuk pengelolaan limbah, emisi GRK, serta perlindungan kawasan hutan dan gambut.
- Perlindungan ketenagakerjaan, meliputi K3, kesejahteraan, non-diskriminasi, dan kebebasan berserikat.
- Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
- Transparansi dalam rantai pasok, termasuk kejelasan asal TBS dan harga yang adil.
- Peningkatan berkelanjutan melalui pemantauan izin dan evaluasi program sosial-ekonomi.
Menurut Prayudi Syamsuri, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, ISPO telah mencakup dua elemen krusial dalam regulasi EUDR, yaitu aspek bebas deforestasi dan legalitas. Ini mencerminkan komitmen politik Indonesia dalam mendukung praktik produksi sawit yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Namun demikian, dalam forum Workstream 2 Joint Task Force (JTF), ditemukan sejumlah kesenjangan antara ISPO dan persyaratan EUDR. Beberapa isu yang disoroti mencakup perbedaan definisi hutan, batas waktu (cut-off date), ketentuan geolokasi, izin pembukaan lahan, syarat penanaman baru, aspek hukum, ketertelusuran, serta sistem rantai pasok dalam skema ISPO.
Sebagai tindak lanjut, Uni Eropa akan melakukan evaluasi terhadap ISPO dan MSPO (Malaysia Sustainable Palm Oil) untuk menilai tingkat kesesuaiannya dengan regulasi EUDR. Sementara itu, Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam rangka menutup kesenjangan tersebut, guna memastikan keberlanjutan perdagangan komoditas sawit ke pasar Eropa.
Baca juga: Tindak Pidana yang Tidak Perlu Ditahan Menurut KUHAP namun Tetap Ditahan oleh Penyidik
Pemerintah Indonesia pun telah menyiapkan rencana aksi: revisi ISPO (penyederhanaan, cakupan hulu–hilir, wajib/mandatory), percepatan e-STDB untuk pekebun, fasilitasi penerapan ISPO, serta pembangunan dashboard nasional untuk ketertelusuran. Selain itu, disiapkan skema sertifikasi nasional untuk kakao, karet, dan kopi, serta penundaan penerapan EUDR bagi pekebun hingga 31 Desember 2025.11
C. Suggestion
Terlepas dari kompleksitas permasalahan yang Indonesia hadapi ketika ingin memenuhi kebijakan EUDR, Indonesia tetap harus menerapkan tujuan mulia yang dikemukakan dalam Article 1 Regulation (EU) 2023/1115, yakni meminimalkan kontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan di seluruh dunia, dan dengan demikian berkontribusi pada pengurangan deforestasi global serta mengurangi kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan hilangnya keanekaragaman hayati secara global.12
Oleh karena itu, penulis menyarankan bagi pembuat kebijakan negara Indonesia untuk:
- Pemerintah wajib untuk berkomitmen dalam mengurangi deforestasi di Indonesia;
- Membuat roadmap terkait langkah konkrit yang akan dilaksanakan dalam 20 tahun kedepan untuk mengurangi kerusakan lingkungan di Indonesia;
- Penguatan kapasitas dan dukungan untuk smallholders atau petani kecil;
- Memperketat pengawasan terhadap peraturan yang sudah berlaku saat ini maupun di masa mendatang.
D. Conclusion
Implementasi EUDR merupakan tantangan besar sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola lingkungan dan memastikan keberlanjutan komoditas ekspor. Meskipun masih terdapat banyak kendala regulasi, teknis, dan sosial, penundaan penerapan EUDR membuka ruang untuk memperkuat sistem traceability, legalitas, dan keberlanjutan yang lebih inklusif bagi petani kecil. Kerjasama dengan Uni Eropa dan negara tetangga serta upaya penguatan skema sertifikasi seperti ISPO menjadi langkah penting untuk menutup kesenjangan dan menyesuaikan standar agar sesuai dengan tuntutan global.
Akhirnya, EUDR bukan semata dianggap sebagai aturan dagang yang memberatkan negara lain, melainkan sebagai pengingat akan rapuhnya tata kelola lingkungan di Indonesia. Penundaan hingga tahun 2025 seharusnya dijadikan sebagai langkah terakhir untuk berbenah. Komitmen nyata pemerintah dalam memperkuat tata kelola komoditas, mulai dari transparansi, penguatan petani kecil, hingga konsistensi penegakan hukum, akan menentukan posisi Indonesia ke depan. Dengan langkah serius ini, Indonesia tidak hanya merespons tekanan eksternal, tetapi juga membuktikan kesungguhannya menjaga lingkungan dan masa depan dunia internasional.
- European Parliament and of the Council, “Regulation (EU) 2023/1115 on the making available on the
Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with
deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010,” Official Journal of
the European Union, 9 Juni 2023. ↩︎ - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1). ↩︎
- https://fwi.or.id/persoalan-deforestasi-di-indonesia-sebuah-polemik/, [diakses pada 27/09/2025] ↩︎
- Madani, “Membangun Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa
melalui Perbaikan Tata Kelola dan Kemitraan yang Inklusif”, https://madaniberkelanjutan.id/publications/test3/ [diakses pada 28/09/2025] ↩︎ - Satyabumi, Penundaan EUDR dan Mengapa ini juga Kekalahan untuk Indonesia, https://satyabumi.org/penundaan-eudr-dan-mengapa-ini-juga-kekalahan-untuk-indonesia/, 2025. ↩︎
- ibid. ↩︎
- Dr. Ir. Tungkot SIpayung, Diskriminasi Sawit EUDR Potensial Melanggar Prinsip WTO, Palm Oil
Agribusiness Strategic Policy Institute, 2024. https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/eudr-potensial-langgar-wto/ ↩︎ - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Siaran Pers
HM.4.6/124/SET.M.EKON.3/04/2024, April 2024 ↩︎ - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Siaran Pers HM.4.6/197/SET.M.EKON.3/06/2024, Juni 2024. ↩︎
- 10Redaksi InfoSawit, https://www.infosawit.com/2024/12/19/akademisi-dan-peneliti-kritik-sistem-informasi-dasbor-nasionalkurang-transparansi-rentan-moral-hazard/, 2024 ↩︎
- Ditjenbun, https://ditjenbun.pertanian.go.id/ispo-diyakini-sudah-penuhi-persyaratan-eudr/, 2024 ↩︎
- Regulation (EU) 2023/1115 ↩︎