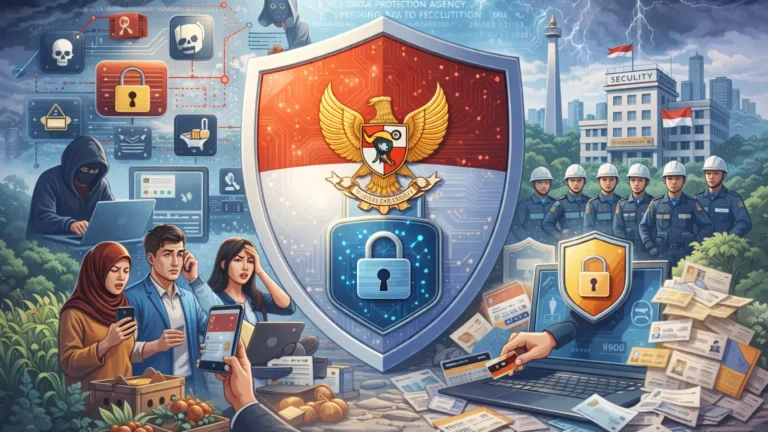Pendahuluan: Indonesia dalam Pusaran Krisis Iklim dan Reputasi Global
Indonesia berada di ambang tenggat penting dalam menentukan arah kebijakan iklim nasional. Jika tidak mampu memperbarui dan menyampaikan komitmen kontribusi nasional dalam pengendalian perubahan iklim sebelum September 2025, maka posisi Indonesia di mata dunia akan terganggu. Negara-negara dalam kelompok 20 ekonomi utama dunia sudah melangkah maju, sementara Indonesia masih bergulat dengan sinkronisasi kebijakan lintas sektor.
Padahal, peluang ekonomi dan lingkungan sangat terbuka. Indonesia memiliki hutan tropis terluas di Asia Tenggara, wilayah laut yang luas dengan padang lamun dan hutan mangrove penyerap karbon, serta sistem Bursa Karbon yang telah resmi diluncurkan. Namun semua itu akan sia-sia jika tidak disertai dengan kepastian hukum, tata kelola yang kredibel, dan keberanian politik untuk mengeksekusi transformasi secara konsisten.
Target pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia tidak main-main: sebesar 49 persen pada 2035 dari baseline 2023. Proyeksi teknokratis telah disusun melalui pemodelan Global Change Analysis Model (GCAM) dan Low Carbon Development Indonesia (LCDI) yang menunjukkan bahwa target ini dapat dicapai melalui penghentian dini pembangkit listrik tenaga uap berbahan batu bara, elektrifikasi sektor transportasi, serta transisi menuju energi terbarukan.
Namun, pendekatan teknis semata tidak cukup. Komitmen tersebut harus memiliki legitimasi administratif, hukum, dan fiskal. Tanpa dasar hukum yang kuat antar-kementerian serta tanpa integrasi dalam dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah nasional, arah kebijakan iklim Indonesia akan mudah berubah tergantung kepemimpinan dan anggaran tahunan. Perlu dipastikan bahwa seluruh kebijakan iklim ini menjadi prioritas nasional yang berkelanjutan lintas pemerintahan dan tidak berhenti di meja pertemuan.
Dasar Hukum Utama Kebijakan Iklim dan Karbon di Indonesia:
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change;
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Laksana Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bursa Karbon.
Bagaimana Nasib Pasar Karbon Indonesia Saat Ini?
Bursa Karbon Indonesia memang telah diluncurkan sejak September 2023. Namun, volume perdagangannya masih sangat kecil dan terbatas pada proyek uji coba sektor kehutanan dan energi. Beberapa penyebab stagnasi tersebut meliputi:
- Regulasi yang tumpang tindih antar kementerian: Kementerian Lingkungan Hidup memegang mandat utama pengurangan emisi, namun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatur emisi dari pembangkit, sementara Kementerian Keuangan mengatur instrumen fiskal, dan Otoritas Jasa Keuangan mengatur bursa. Belum ada satu kerangka integratif yang mengikat mereka secara fungsional;
- Tidak adanya peta jalan karbon sektoral yang seragam: Misalnya, sektor transportasi dan industri belum memiliki baseline dan proyeksi pengurangan emisi yang dapat diverifikasi, membuat tidak sinkron dengan registrasi nasional emisi yang ada;
- Lembaga verifikasi dan registrasi terbatas: Saat ini hanya sedikit lembaga yang terakreditasi untuk verifikasi karbon di Indonesia, sebagian besar masih menggandeng verifikator luar negeri. Hal ini meningkatkan biaya dan memperpanjang proses validasi proyek karbon;
- Sistem SRN-PPI belum maksimal secara nasional: SRN-PPI sebagai platform pendaftaran dan pemantauan aksi mitigasi karbon hanya aktif penuh di tingkat pusat. Belum terintegrasi dengan sistem informasi lain seperti DJP Kemenkeu seputar pajak karbon, sector swasta tidak berani berdagang karbon akibat regulasi yang tumpeng tindih. Banyak provinsi belum memiliki kapasitas teknis maupun kelembagaan untuk mendaftarkan proyeknya, menyebabkan potensi lokal tidak tercatat dan tidak bisa diperdagangkan.
Aspek hukumnya tidak sederhana. Perdagangan karbon menyentuh:
- Hukum perdata: karena melibatkan objek tidak berwujud yang dipertukarkan secara sah (Pasal 499 dan 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- Hukum administrasi negara: karena setiap transaksi harus terdaftar dan diverifikasi melalui SRN-PPI dan instansi terkait;
- Hukum lingkungan: karena dampaknya harus terukur secara ilmiah dan dapat diverifikasi melalui prinsip kehati-hatian (precautionary principle);
- Hukum tata negara: karena skema kompensasi emisi lintas negara memerlukan pertanggungjawaban negara dan pengakuan internasional.
Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market): Peluang yang Belum Berpihak pada Rakyat
Mekanisme pasar karbon sukarela atau voluntary carbon market (VCM) memungkinkan pihak swasta membeli kredit karbon dari proyek yang berhasil menurunkan emisi di luar kewajiban regulasi. Skema ini seharusnya membuka peluang besar bagi masyarakat adat, petani, dan komunitas lokal untuk memperoleh insentif dari upaya konservasi yang mereka lakukan.
Namun realitanya, pasar karbon sukarela di Indonesia masih belum berpihak pada rakyat. Masalah utama yang mengemuka antara lain:
- Mayoritas proyek karbon menggunakan skema dan standar internasional tanpa konsultasi publik lokal;
- Biaya sertifikasi proyek sangat tinggi dan hanya bisa diakses oleh pelaku besar yang punya koneksi ke lembaga validasi internasional;
- Ketiadaan aturan nasional membuat masyarakat tidak punya kekuatan hukum ketika proyek merugikan lingkungan atau ruang hidup mereka;
- Lemahnya pengawasan membuat banyak proyek beroperasi tanpa redistribusi manfaat ke komunitas penjaga hutan atau pesisir.
VCM tanpa regulasi nasional yang jelas akan menciptakan ketimpangan baru. Negara seharusnya hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai pelindung hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang adil.
Skema Hukum yang Dapat Didorong oleh Masyarakat
Alih-alih menunggu perubahan dari atas, masyarakat memiliki ruang legal untuk menekan pemerintah agar bertindak. Beberapa langkah hukum yang dapat dilakukan antara lain:
- Pengajuan hak uji materi (judicial review) terhadap aturan turunan yang tidak mengakomodasi keadilan iklim;
- Permohonan informasi publik terhadap daftar proyek VCM dan kredit karbon dalam SRN-PPI berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- Gugatan perdata atau citizen lawsuit terhadap proyek karbon yang melanggar hak lingkungan hidup komunitas lokal;
- Pelibatan aktif dalam perumusan regulasi melalui forum konsultasi publik dan musyawarah daerah, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan prinsip-prinsip partisipasi dalam pembangunan.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut menjadi pemegang hak, pelaksana, dan pengawas kebijakan iklim nasional.
Baca juga: Komitmen Pemerintah melindungi Aktivis Lingkungan Hidup
Penutup: Menjaga Kepastian Hukum demi Keadilan Iklim
Kebijakan iklim bukan sekadar dokumen pelaporan internasional. Ia adalah refleksi tanggung jawab negara dalam menjamin keberlanjutan hidup dan keadilan antargenerasi. Dalam konteks krisis iklim global, ketegasan Indonesia untuk menyelaraskan visi hukum, ekonomi, dan lingkungan akan menentukan nasib jutaan orang di masa depan.
Indonesia tidak butuh janji iklim. Indonesia butuh sistem yang bekerja, hukum yang hidup, dan keberanian politik untuk melindungi bumi dan rakyatnya.