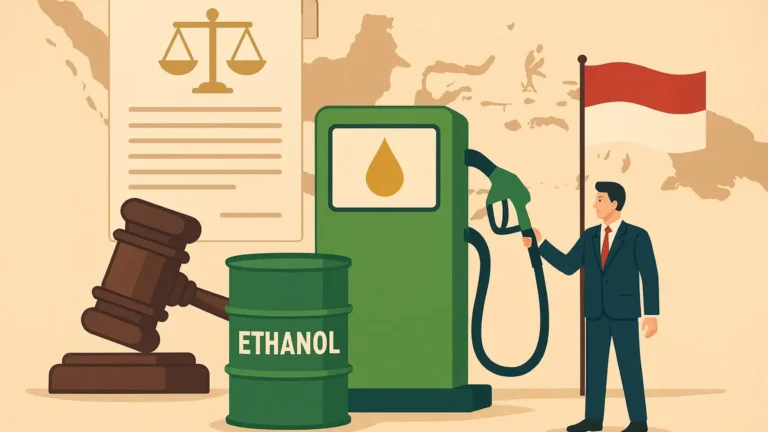Pernyataan Prabowo yang melabeli rakyat dengan istilah terorisme, makar, hingga ekstremisme jelas tidak pantas keluar dari mulut seorang negarawan. Rakyat bukan sedang berkhianat, mereka hanya sedang menuntut kembali kedaulatan yang memang hak mereka sejak awal. Sayangnya, konferensi pers hari ini justru menggambarkan amnesia sejarah: lupa bahwa gerakan rakyat selalu lahir sebagai respons atas akumulasi ketidakadilan negara.
Kita kembali disuguhi skenario lama ala Orde Baru: cipta kondisi, tuduhan makar, dan retorika keamanan nasional. Ironisnya, sosok yang dulu ikut membidani lahirnya RUU TNI yang kini cacat formil sedang diuji di Mahkamah Konstitusi seolah lupa bahwa bayang-bayang Dwi Fungsi ABRI masih menghantui politik kita hingga hari ini. Reformasi 1998 jelas mengamanatkan pemisahan militer dari politik, tetapi gaya lama itu enggan mati, hanya berganti wajah, bukan hilang.
Di lapangan, protes rakyat tidak bisa disederhanakan sebagai kerusuhan. Aksi itu juga menyinggung soal rancangan KUHAP yang berusaha memangkas kewenangan polisi, lemahnya mekanisme penegakan etik di DPR, hingga wajah oligarki yang semakin telanjang dalam politik kita. Namun pemerintah tidak menyentuh akar masalah. Solusi instan yang ditawarkan hanya berupa penonaktifan anggota DPR yang bermasalah. Padahal jika kita membuka UU MD3, istilah nonaktif itu tidak ada. Yang dikenal hanya pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 239 dan 240. Artinya, langkah ini hanya kosmetik politik, manuver untuk menipu publik dengan bahasa hukum palsu.
Lebih jauh, mekanisme recall anggota DPR pun bermasalah. Saat ini kewenangannya hanya ada di tangan partai politik, bukan rakyat pemilih. Padahal UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 sudah jelas menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi, kenapa partai seenaknya menarik mandat? Bukankah kursi itu seharusnya milik konstituen, bukan sekadar jatah elite partai? Inilah bentuk paling nyata bagaimana partai politik justru mencuri hak rakyat, lalu menggunakannya sebagai alat tawar-menawar kekuasaan.
Standar ganda pemerintah membuat rakyat semakin muak. Rakyat dilarang keras melakukan kekerasan, tetapi aparat bebas represif di jalanan. Hak rakyat untuk menyampaikan pendapat yang dijamin Pasal 28E UUD 1945 justru dikriminalisasi dengan label makar. Publik dipaksa diam, sementara elite pesta pora dengan akumulasi kekayaan. Setiap aksi rakyat dibungkam, tetapi setiap skandal kekayaan pejabat atau pelanggaran etika anggota dewan selalu ditutup-tutupi dengan dalih hukum dan mekanisme internal.
Baca juga: Birahi Politik Kekuasaan
Persoalan bangsa ini juga tidak bisa direduksi hanya pada gaji DPR yang kelewat tinggi atau gaya hidup pejabat yang mempertontonkan kemewahan. Masalah sesungguhnya ada pada sistem politik yang dikuasai oligarki, UU Pemilu yang sengaja dibiarkan usang, dan partai politik yang pragmatis mengusung pengusaha serta artis tanpa proses kaderisasi. Inilah sebabnya DPR hasil pemilu kita sering disebut tidak bermutu. Bedanya apa dengan era Jokowi? Nyaris tidak ada. Sama-sama lahir dari sistem yang rusak, sama-sama gagal menghasilkan parlemen yang bermartabat.
Sekarang kita tahu kenapa RUU yang masuk prolegnas prioritas sangat sulit untuk di sahkan selama 10 tahun terakhir, jawabannya ialah anggota dewannya tidak bermutu, lulusan SMA tau apa tentang pembuatan UU, pembentukan UU dan pengesahan UU. Ketidakmutuan itu menghambat proses bernegara dan melahirkan kebodohan yang nyata di parlemen. Karena proses pembentukan UU itu hanya di dapat di fakultas hukum danyang tahu hanya yang pernah menjadi mahasiswa, bukan pragmatis menjadi anggota dewan dari artis atau piaraan oligarki yang tidak paham legislasi.
Rakyat harus sadar bahwa musuh utama bukan mahasiswa, bukan ojek online, bukan tetangga yang ikut turun ke jalan. Musuh sejati adalah elite politik yang terus mempertahankan status quo dengan instrumen negara. Reformasi setengah hati yang kita jalani selama dua dekade terakhir hanya melahirkan demokrasi semu, di mana oligarki justru semakin kuat. Jalan keluarnya hanya satu: reformasi menyeluruh melalui revisi UU Pemilu, pembenahan partai politik, dan pengembalian hak recall ke konstituen. Tanpa itu, rakyat akan terus menjadi korban dari sistem yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan elite.
Kedaulatan rakyat tidak boleh lagi dicuri dengan narasi makar, terorisme, atau keamanan negara. Konstitusi sudah jelas bicara: kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di kantong elite partai, apalagi oligarki. Menyebut rakyat sebagai teroris hanya akan mempertebal jurang ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Rakyat turun ke jalan bukan untuk menghancurkan republik, melainkan untuk mengingatkan bahwa republik ini berdiri di atas keringat mereka.
Bila negara gagal mendengar suara itu, gerakan konstitusional rakyat akan menjadi satu-satunya jalan untuk merebut kembali apa yang seharusnya: kedaulatan yang asli, murni, dan tidak boleh dinegosiasikan.