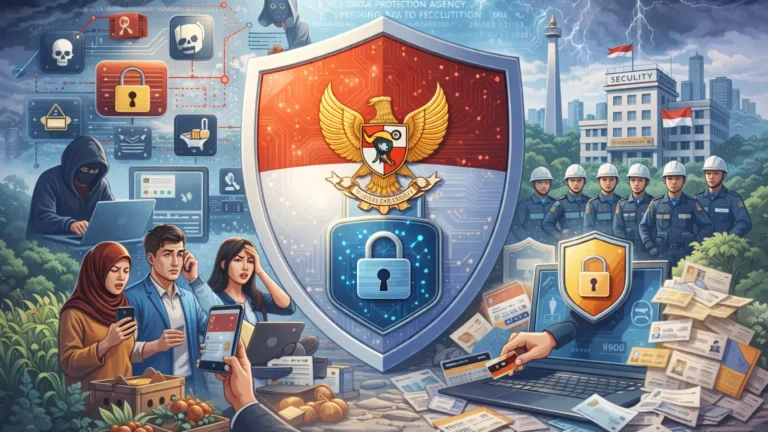Pemberian abolisi dan amnesti kepada dua figur yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi, yaitu TL dan HK, secara kasat mata tampak sebagai langkah inkonstitusional yang membajak semangat pemberantasan korupsi. Konstitusi memang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD NRI 1945, namun kewenangan itu bukan kekuasaan absolut. Kewenangan tersebut harus ditafsirkan dan dijalankan dalam koridor prinsip negara hukum, asas keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik.
Menurut Asas Legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas Due Process of Law, pemberian pengampunan hukum tidak boleh melampaui prinsip kehati-hatian hukum dan tidak boleh dilakukan dengan motivasi politis semata. Dalam kasus TL dan HK, publik mempertanyakan mengapa mekanisme hukum seperti Peninjauan Kembali (PK) atau grasi yang masih tersedia tidak dipakai lebih dulu. Apalagi dalam kasus HK, unsur suap dan pelarian buronan KPK sangat terang, sehingga pemberian amnesti terhadap korupsi ini sangat bertentangan dengan semangat UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).
Menurut Prof. Mahfud MD, pemberian amnesti dan abolisi terhadap kejahatan luar biasa seperti korupsi tidak memiliki dasar hukum kuat, karena amnesti dan abolisi sejatinya diperuntukkan untuk tindak pidana politik, bukan kejahatan ekonomi yang merugikan negara. Ini sejalan dengan Putusan MK No. 28/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa kewenangan konstitusional Presiden tidak boleh melampaui asas proporsionalitas dan kepentingan umum. Dalam konteks ini, Presiden dan DPR justru diduga telah menyalahgunakan kewenangan konstitusional untuk tujuan politis, bukan keadilan hukum.
Secara teori, Lon L. Fuller dalam The Morality of Law menyatakan bahwa keabsahan suatu produk hukum ditentukan oleh moralitas internal hukum itu sendiri: konsistensi, kejelasan, dan akuntabilitasnya. Jika suatu produk hukum digunakan untuk menyelamatkan elite yang korup, maka ia telah kehilangan moralitas hukum dan menjadi sarana legalisasi impunitas. Jeremy Bentham bahkan lebih tajam: hukum yang tak adil lebih buruk daripada ketidakadilan tanpa hukum, karena ia membungkus kezaliman dalam jubah legalitas.
Baca juga: Putusan MK Dibuat untuk Melayani Dinasti
Dari perspektif hukum tata negara, langkah ini mencerminkan penyimpangan prinsip checks and balances, karena DPR tidak lagi menjadi lembaga pengawas eksekutif, tetapi menjadi kolaborator dalam penyelamatan elite. Padahal, jika kita merujuk pada asas perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka seharusnya pelaku korupsi diproses secara setara, tanpa intervensi politik.
Pertanyaan mendasar adalah: mengapa Presiden dan DPR memilih jalan amnesti dan abolisi padahal masih terbuka pintu hukum lain seperti PK dan grasi? Muncul dugaan bahwa langkah ini dilakukan untuk mencegah dua tokoh tersebut membongkar keterlibatan elite kekuasaan yang cawe-cawe dalam pusaran korupsi. Dengan kata lain, pemberian amnesti atau abolisi bukan tindakan penyelamatan hukum, melainkan penyelamatan politik.